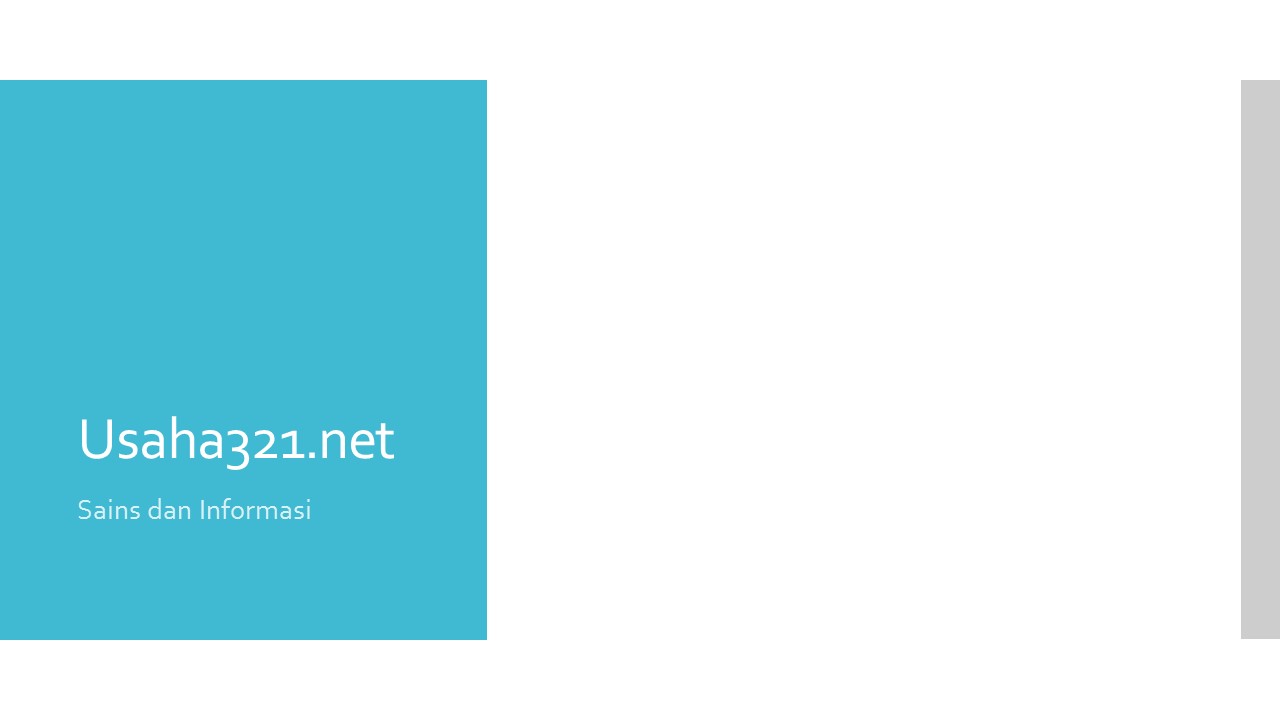Revolusi Hijau dan Ketimpangan Sosial di Pedesaan India!
Revolusi hijau telah menjadi orientasi dominan untuk program pembangunan pedesaan di India selama lebih dari dua dekade sekarang. Sebagai strategi, hal itu menyiratkan pengenalan varietas unggul, penggunaan mesin pertanian secara ekstensif, irigasi sumur yang berenergi, penggunaan pupuk dan pestisida dosis tinggi yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Secara optimis diperhitungkan bahwa dari sini akan muncul solusi abadi untuk masalah abadi kemiskinan dan kelaparan pedesaan.
Makalah ini mengkaji literatur luas yang telah terakumulasi tentang revolusi hijau dengan maksud untuk menentukan sifat dampak dari strategi pembangunan di berbagai bagian masyarakat pedesaan. Apakah revolusi hijau berhasil mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di pedesaan India? Sejak tahun 1967 ketika Program Varietas Hasil Tinggi (bibit) (HYVP) secara sadar diperkenalkan di pertanian India, banyak tulisan yang mendukung dan menentang revolusi hijau. Akan tetapi, keliru jika menyamakan revolusi hijau dengan HYVP saja.
Revolusi hijau harus dipahami lebih sebagai ideologi transformasi pedesaan yang lebih luas sedangkan program-program seperti HYVP, IRDP (Program Pembangunan Pedesaan Terpadu) dan sejenisnya adalah langkah-langkah khusus yang dilembagakan untuk menerjemahkan ideologi revolusi hijau ke dalam praktik (Parthasarthy). Bahkan dengan risiko tampak menyatakan hal yang sudah jelas dan agak sederhana, perlu ditekankan bahwa revolusi hijau sebagai sebuah paket (ideologi dan program) harus didefinisikan sebagai “penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam skala besar untuk pertanian”.
Teknologi revolusi hijau melibatkan penggunaan ekstensif mesin pertanian (sebagai perangkat efisien hemat tenaga kerja), benih hibrida (berhasil tinggi), irigasi sumur berenergi (dan irigasi angkat), penggunaan dosis pupuk dan pestisida yang tinggi, dan sejenisnya. Singkatnya, “penggunaan teknologi produksi yang ditingkatkan dan varietas unggul benih secara ekstensif dan intensif” telah menjadi inti dari revolusi hijau.
Meskipun dengan perbedaan derajat, bagian pedesaan India yang berbeda telah bersenandung dengan aktivitas pembangunan. Langkah-langkah awal untuk pembangunan pedesaan dalam bentuk program pengembangan masyarakat, reformasi tanah dan lembaga koperasi, yang diperkenalkan dalam dua dekade pertama (1947-67) kemerdekaan, tidak terlalu efektif baik dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara substansial atau dalam menghilangkan momok kemiskinan pedesaan, pengangguran dan juga ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang terus tumbuh (Dhanagare).
Revolusi hijau—paket teknologi yang disponsori AS untuk pembangunan pertanian—diterima di India secara berlebihan dan juga tanpa kritik. Diharapkan bahwa dengan produksi pertanian yang lebih baik, tidak hanya solusi abadi akan ditemukan untuk masalah kemiskinan dan kelaparan pedesaan yang terus-menerus tetapi juga akan menghasilkan basis sumber daya baru — landasan peluncuran untuk industrialisasi pedesaan yang akan menciptakan peluang kerja baru dan akan meningkatkan kualitas hidup di akar rumput dalam ukuran yang cukup berarti.
Revolusi hijau—teori dan praktik—telah menjadi orientasi yang dominan, dan juga banyak dibicarakan, untuk program pembangunan pedesaan di India selama hampir dua dekade sekarang (sejak 1967). Sementara itu, dua tinjauan jangka menengah atas hasil bersih dan dampak revolusi hijau di pedesaan India dicoba oleh dua lembaga sukarela yang terpisah pada awal tahun 1970-an, yaitu hanya dalam waktu lima tahun sejak diperkenalkannya HYVP dan program serupa lainnya.
Salah satunya dalam bentuk simposium yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perubahan Sosial pada tahun 1973 (CSSC, 1974). Itu menyoroti aspek positif dan negatif dari revolusi hijau. Sisi positifnya diklaim bahwa dampak revolusi hijau terlihat pada produksi biji-bijian pangan yang telah meningkat di India pada periode pasca-HYVP (1967-73) sebesar 19,1 persen selama periode pra-HYVP (1961-65). ).
Peningkatan ini mencapai 87,2 persen di Punjab, dan 64,90 persen di Haryana di mana peningkatan kinerja produksi sangat mengesankan (Vyas). Oleh karena itu, beberapa sarjana kemudian berperilaku bahwa untuk memperbaiki daerah terbelakang pada umumnya, dan pertanian pada khususnya, tidak ada alternatif lain selain revolusi hijau (CSSC). Namun, gambaran indah ini tidak didukung bahkan oleh para protagonisnya yang setia. Misalnya, ditegaskan pada simposium CSSC bahwa revolusi hijau benar-benar tidak terjadi, bahwa teknologi pertanian baru hanya dapat diakses oleh petani besar dan bahwa kemakmuran yang dihasilkan oleh revolusi hijau didistribusikan secara berbeda ke kategori petani yang berbeda. menempatkan petani kecil dan marjinal pada posisi yang relatif tidak menguntungkan.
Alasan untuk distribusi diferensial jelas . Teknologi sereal hasil tinggi/berbiaya tinggi dari revolusi hijau membutuhkan investasi modal yang besar, umumnya di luar kemampuan mayoritas petani kecil dan marjinal.
Tinjauan kedua dilakukan pada tahun 1973 oleh Halslemere Declaration Group (HDG) yang berbasis di London. Laporannya menyerang revolusi hijau sebagai propagandis dan cara yang sangat menyesatkan untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5 persen dalam gandum yang dicapai di Punjab dan Hary ana dari tahun 1967 hingga 1973 dengan diperkenalkannya HYVP ketika tingkat pertumbuhan gabungan biji-bijian makanan tahunan di India, menggunakan varietas benih yang ditingkatkan secara lokal, sekitar 3 persen.
HDG lebih lanjut mengkritik pemerintah India karena membuat subsidi yang dilembagakan dan kredit murah serta fasilitas serupa lainnya yang relatif lebih mudah diakses oleh pemilik tanah besar/petani kaya daripada petani kecil dan marjinal. Laporan HDG memang mengakui bahwa di Punjab dan Haryana efek menetes dari revolusi hijau sebagian terlihat dalam upah harian yang lebih baik (untuk buruh tani) yang meningkat sebesar 89 persen dari tahun 1961 sampai 1968. Namun, ‘apa yang disebut’ keuntungan ini sepenuhnya diimbangi oleh kenaikan harga (sekitar 93% selama periode yang sama) meskipun produksi pertanian meningkat secara substansial.
Dalam pandangan kami, kedua ulasan yang dibahas di atas merupakan penilaian awal terhadap revolusi hijau di India. Hingga tahun 1973, langkah-langkah revolusi hijau telah diperkenalkan hanya di beberapa daerah terpilih yang kecenderungan untuk mengadopsi teknologi pertanian baru merupakan fakta yang sudah mapan. Selain itu, masa percobaan selama lima tahun (dari tahun 1967 sampai 1973) terlalu singkat untuk dinilai adil. Setelah itu, beberapa studi telah melaporkan temuan mereka mengungkapkan kompleksitas dampak yang tepat dari langkah-langkah revolusi hijau, hasil pertanian per hektar, upah, total pendapatan rumah tangga dari berbagai kategori petani, pola konsumsi dan juga pengentasan kemiskinan pedesaan di umum. Literatur penelitian ini telah tumbuh menjadi tubuh yang masif.
Sebuah upaya dilakukan untuk menyaring beberapa bahan ini dengan maksud untuk memeriksa sifat dampak revolusi hijau di berbagai lapisan masyarakat pedesaan. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pembangunan ini telah berhasil atau tidak dalam mengangkat sebagian besar kaum miskin pedesaan di atas garis kemiskinan dan dalam mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi di pedesaan India. Latihan ini didasarkan pada penggunaan bahan sumber sekunder. Tentu saja peneliti yang berbeda telah menggunakan ukuran yang berbeda untuk memenuhi syarat ‘pertumbuhan’ atau ‘dampak’.
Karena ukuran kuantitatif seperti itu lebih sering menimbulkan ketidaksepakatan di antara para ekonom daripada menimbulkan kesamaan pendapat, kumpulan data yang sama digunakan dan dapat digunakan untuk mendukung dan mempertahankan sudut pandang atau interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, studi tentang dampak revolusi hijau telah dilaporkan dari berbagai wilayah geopolitik di India. Tidak semua daerah berada pada tingkat pembangunan yang sama.
Variasi regional dalam struktur sosial agraria—penguasaan lahan dan pola penggunaan lahan, kondisi agroklimat dan sosio-kultural lainnya serta kekhususan sejarah setidaknya sebagian dapat menjelaskan beberapa persamaan di pedesaan India yang dibahas dalam makalah ini. Oleh karena itu, tidak disarankan di sini bahwa semua ketidaksetaraan pedesaan di berbagai wilayah di India dapat dikaitkan dengan revolusi hijau.
langkah-langkah yang diarahkan oleh negara yang tidak merata yang dibahas dalam artikel ini. Juga akan sulit untuk mempertahankan klaim bahwa latihan semacam itu, atau bahkan, bisa, benar-benar bebas nilai. Meskipun demikian, kami telah mencoba penilaian revolusi hijau ini dengan harapan bahwa ini akan memberi kami setidaknya jawaban kualitatif atas pertanyaan kami dan akan menyarankan garis masa depan untuk strategi pembangunan pedesaan di India.
Awalnya, langkah-langkah revolusi hijau dianggap ‘skala-netral’. Oleh karena itu, diharapkan apakah itu benih HYV, pestisida, insektisida dan pupuk, atau apakah itu irigasi angkat, mekanisasi operasi pertanian dan subsidi pertanian lainnya, pemilik tanah kecil akan mendapat manfaat sebanyak pemilik tanah yang lebih besar, jika tidak lebih. .
Namun, birokrasi pembangunan pertanian yang bekerja di akar rumput memiliki persepsi yang berbeda. Pemahaman mereka jarang disesuaikan dengan gagasan netralitas-skala dan tindakan mereka hampir selalu mencerminkan kebijakan pembangunan pedesaan pro-kaya yang diam-diam.
Joan Mencher (1978), misalnya, telah melaporkan bahwa sebagian besar petugas pertanian yang dia wawancarai di distrik Chingleput Tamil Nadu tampak jauh dari netral. “Apa yang menurut mereka diperlukan untuk memajukan revolusi hijau adalah melupakan petani kecil (yakni, pemilik kurang dari 5 acre lahan beririgasi—didefinisikan sebagai kepemilikan yang tidak ekonomis), karena mereka tidak dapat benar-benar berkontribusi pada peningkatan produksi. Kepada para pejabat ini petani progresif adalah mereka yang memiliki pertanian yang layak dan yang cukup kaya” (Mencher, 1978: 239-40).
Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Mencher menemukan bahwa beberapa petani kecil di Chingleput tertarik untuk mencoba input baru dan seinovatif pemilik tanah yang kaya. Namun yang pertama seringkali kekurangan fasilitas untuk mencoba cara-cara baru, dan jarang mendapat dorongan dari birokrasi pembangunan. Proyek Benih Nasional, yang dimulai di India dengan bantuan Bank Dunia pada tahun 1976 sebagai bagian dari langkah-langkah revolusi hijau, adalah contoh lain bagaimana strategi pembangunan pedesaan dibangun di atas asumsi yang sama (pro-kaya). Produksi dan pemasaran benih HYV untuk meningkatkan produksi di bidang pertanian telah menjadi tujuan proyek ini.
Implementasi sebenarnya dari skema ini—bagian integral dari revolusi hijau telah diselidiki secara kritis oleh Satya Deva (1980) mengambil kasus spesifik dari Haryana Seeds Development Corporation. Kebijakan yang mendasari proyek ini adalah mendukung perluasan sektor swasta untuk menjaga keseimbangan yang wajar antara sektor publik dan swasta di bidang pertanian. Para petani di wilayah proyek (masing-masing 9 blok berisi sekitar 100 desa) akan membeli dua bagian senilai Rs. 100 masing-masing per hektar lahan penghasil benih; uang bagi hasil dibayarkan selama lima kali panen (Deva, 1980: 263-65). Dalam waktu empat tahun pendirian Perusahaan Benih di Haryana, ada 285 penanam benih pemegang saham. Sekitar sepertiga dari jumlah tersebut menanam benih di petak seluas masing-masing 5 acre; sepertiga lainnya di petak seluas 5-10 acre; sepertiga sisanya menggunakan petak yang lebih besar berkisar antara 10 dan 100 acre (Deva, 1980: 265). Karena benih ditanam secara umum hanya di sebagian dari kepemilikan tanah mereka yang lebih besar, jelaslah bahwa sebagian besar petani kaya dengan kepemilikan yang besar mendapat manfaat dari proyek tersebut.
Lagi pula, syarat-syarat kesepakatan yang mengharuskan seorang petani membeli dua saham (masing-masing Rs. 100) per acre menguntungkan petani kaya. Dan bagaimanapun juga, penanam benih terkecil sekalipun (dengan lahan seluas 5 acre untuk budidaya benih) membutuhkan investasi awal sebesar Rs. 1.000 modal saham jika dia ingin mendapatkan keuntungan dari skema ini.
Mengenai pemanfaatan benih, survei terhadap 60 pengguna dan 73 non-pengguna benih gandum bersertifikat juga mengungkapkan beberapa fakta menarik tentang disparitas pertumbuhan di daerah revolusi hijau. “Ditemukan bahwa pengguna hanya berasal dari kalangan pemilik tanah dan petani kasta tinggi dan tidak ada satu pun yang berasal dari kalangan penggarap atau kasta rendah (terjadwal)”.
Tidak salah lagi, kesimpulan Satya Deva menunjukkan bahwa pengembangan pertanian melalui penerapan pengetahuan ilmiah baru hanyalah sebuah eufemisme untuk menggunakan sektor publik untuk mempromosikan industri benih swasta di mana manfaat dari pengetahuan ilmiah baru itu secara bervariasi jatuh ke kasta atas pedesaan yang kaya. petani; jarang menjangkau penyewa miskin dan petani kasta rendah yang paling membutuhkannya (Deva, 1980: 269). Introduksi benih varietas unggul sebagai input di daerah revolusi hijau dengan demikian merupakan ukuran lain yang menciptakan jenis ketidaksetaraan baru, dan terkadang menambah ketidaksetaraan lama.
Bias Petani Pro-Kaya:
Bias petani pro-kaya dari perencanaan pembangunan pedesaan India menarik pembenarannya dari kekeliruan bahwa teknologi revolusi hijau, yang padat modal, lebih cocok untuk petani kaya daripada petani kecil dan marjinal karena hanya petani kaya yang memiliki sumber daya yang memadai untuk membeli teknologi itu. produksi, dan bahwa input yang mahal hanya dapat dijangkau oleh petani yang lebih kaya; oleh karena itu, yang terakhir lebih baik ditempatkan untuk memperoleh manfaatnya.
Asumsi ini kemudian dikembangkan menjadi argumen, agak hipotetis, bahwa tingkat hasil keseluruhan serta produktivitas per acre akan berkorelasi positif dengan luas lahan. Kekeliruan bawaan dalam pernyataan ini telah sepenuhnya diledakkan oleh temuan survei perintis yang dilakukan oleh Bhalla dan Chadha (1983) baru-baru ini di Punjab.
Dilakukan di tiga wilayah Punjab yang terpisah, survei ini memilih sekitar 180 desa mengikuti metodologi putaran ke-30 Survei Sampel Nasional dan mengumpulkan data berharga dari 1663 rumah tangga petani. Metodologinya untuk mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam enam kategori, yang dibatasi secara eksklusif oleh ukuran kepemilikan operasional, menderita kekurangan tertentu karena mungkin tidak cukup dekat dengan stratifikasi sosial pedesaan.
Meskipun demikian, temuan survei ini cukup mengungkap. Analisis biaya bahan (yaitu pengeluaran untuk benih, pupuk kandang dan pupuk, pemeliharaan sapi jantan, solar dan listrik, perbaikan dan pemeliharaan peralatan) telah menunjukkan bahwa di ketiga wilayah tersebut, pengeluaran untuk input bahan per acre areal tanam berbanding terbalik. berhubungan dengan ukuran peternakan.
Hal ini mungkin menimbulkan kesan bahwa langkah/input revolusi hijau benar-benar lebih menguntungkan petani kecil dan marjinal daripada petani kaya. Tapi ini akan sangat menyesatkan, karena Bhalla dan Chadha memberi tahu kita bahwa “di peternakan marjinal dan kecil, bagian terbesar dari biaya material adalah pengeluaran untuk ternak kering—sekitar 48,63 persen dari total biaya material yang dikeluarkan oleh petani marjinal. bagi negara secara keseluruhan”. Dalam hal pengeluaran per acre untuk diesel dan listrik; perbaikan dan pemeliharaan mesin kemudian terus meningkat dengan ukuran peternakan.
Apa yang menarik dan penting untuk dicatat adalah bahwa meskipun ketergantungan mereka lebih besar pada masukan modal tradisional (seperti sapi kering), peternakan kecil ternyata melengkapi persediaan produktif mereka sendiri dengan menyewa layanan mesin.
Oleh karena itu, pengeluaran per acre untuk biaya sewa mesin jauh lebih tinggi pada pertanian marjinal dan kecil dibandingkan dengan pertanian ukuran besar (Bhalla et al., 1983: 49-60). Hal ini jelas menunjukkan bahwa petani marjinal dan kecil tidak kekurangan dorongan dan inisiatif, juga tidak kekurangan kecenderungan untuk berinvestasi dan mengambil risiko untuk melakukan perbaikan jangka panjang dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Survei Punjab memperjelas bahwa petani kecil dan marjinal yang bersaing dengan petani kaya merupakan tugas berat, tidak ragu untuk mengambil risiko. Faktanya, mereka cukup giat untuk melakukan segala upaya yang mungkin untuk meningkatkan input pertanian mereka. Namun, inisiatif kewirausahaan petani kecil dan marjinal tampaknya tidak banyak membantu mereka dan juga tidak mampu mengurangi ketidaksetaraan yang tumbuh di pedesaan Punjab.
Distribusi 1.663 rumah tangga dalam survei Punjab menunjukkan beberapa ketidaksetaraan ini. Bhalla dan Chadha menemukan bahwa dalam total sampel mereka ada 140 (8,4%) rumah tangga yang memiliki pertanian marjinal dengan ukuran rata-rata 1,6 acre; di ujung lain dari spektrum adalah 74 (4,4%) peternakan besar dengan ukuran rata-rata 32,8 acre. Dengan demikian, peternakan berukuran besar kira-kira 20 kali ukuran peternakan terkecil (rata-rata).
Ketidaksetaraan seperti itu kemudian dilanggengkan dan diperkuat lebih lanjut oleh preferensi birokrasi pembangunan yang dikenal lebih menyukai pemilik pertanian besar atas dasar asumsi produktivitas tinggi dari pertanian besar. Asumsi ini, bagaimanapun, tidak divalidasi oleh data survei Punjab yang menunjukkan bahwa pendapatan bisnis pertanian (pertanian) per acre adalah Rs. 754,50 untuk peternakan terkecil dan Rs. 740,40 untuk yang terbesar.
Dengan kata lain, ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa petani terkecil setidaknya sama produktifnya jika tidak lebih, seperti petani terbesar. Oleh karena itu, argumen potensi produktif dan efisiensi pertanian besar tidak dipertahankan secara empiris; tentunya tidak dapat memberikan pembenaran yang meyakinkan untuk distribusi yang tidak egaliter dari sumber daya yang langka seperti tanah pertanian serta input melalui langkah-langkah revolusi hijau seperti yang ditemukan di India pada umumnya dan Punjab pada khususnya.
Di India, kebijakan pertanian yang diambil oleh pemerintah sejak tahun 1960-an dan seterusnya juga cenderung meningkatkan tingkat ketimpangan antara daerah-daerah yang beririgasi terus-menerus dan daerah-daerah yang harus bergantung terutama pada curah hujan untuk penanaman. Sudah menjadi fakta umum bahwa pertanian di wilayah barat lebih terlayani dan dijangkau oleh birokrasi negara yang melaksanakan program-program pembangunan daripada di daerah kering.
Hal ini terjadi karena paket revolusi hijau telah dirancang dengan mempertimbangkan terutama pertanian beririgasi abadi. Produksi varietas padi unggul dengan pemupukan dosis tinggi terutama mempengaruhi daerah irigasi yang sudah disukai. Oleh karena itu, dilihat dari rata-rata pendapatan rumah tangga, ketimpangan di pedesaan bahkan lebih mencolok di daerah yang relatif lebih beririgasi dan karenanya lebih makmur.
Beberapa peneliti telah melakukan studi banding tentang perubahan umur ekonomi relatif di daerah basah dan kering. Misalnya, Athreya dan rekan penelitinya telah mempelajari enam sampel desa dari dua serikat panchayat di distrik Tiruchi di Tamil Nadu. Penyelidikan mereka ditujukan untuk mengidentifikasi status kelas dari masing-masing rumah tangga. Sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas ke dalam hubungan produksi, penelitian ini menyelidiki secara komparatif pendapatan rata-rata rumah tangga proletar pedesaan—baik petani miskin maupun buruh tani—di daerah basah dan kering.
Bagi petani miskin pendapatan tunai/upah dari pertanian di lahan basah adalah Rs. 1.458 berbeda dengan Rs. 346 di daerah kering. Disparitas pendapatan di daerah basah dan kering di sini adalah rasio 4,2: 1,0 yang menunjukkan bahwa di daerah basah pendapatan pertanian rumah tangga petani miskin lebih dari empat kali rata-rata pendapatan rumah tangga yang bersangkutan dari daerah kering . Akan tetapi, petani miskin dari daerah kering tampaknya mencari nafkah dengan menambah pendapatan mereka secara substansial melalui sumber-sumber nonpertanian.
Yang lebih mencolok adalah disparitas antara kondisi ekonomi (diukur dengan pendapatan rata-rata) rumah tangga petani miskin dan rumah tangga buruh tani. Kajian oleh Athreya dan lainnya menemukan lebih lanjut bahwa upah tunai dari pertanian yang diperoleh oleh rumah tangga buruh di daerah basah hampir dua kali lipat upah di zona kering.
Namun, jika total pendapatan tunai rumah tangga buruh tani dari semua sumber diperhitungkan, maka disparitas di daerah kering dan basah agak berkurang dengan perbandingan 1:1,5 yang berarti bahwa kondisi ekonomi buruh upahan di daerah basah secara keseluruhan masih satu setengah kali lebih baik daripada buruh di daerah kering. Perkembangan yang paling menarik dari skenario pedesaan bukan hanya bahwa kesenjangan antara kondisi ekonomi di daerah kering dan basah terus melebar, tetapi juga bahwa pendapatan ekonomi rumah tangga buruh tani dengan cepat melampaui pendapatan keluarga petani miskin.
Ini berlaku untuk area basah seperti halnya area kering. Dalam studi Tamil Nadu, yang dilakukan oleh Athreya dan rekannya lagi, ditemukan bahwa total pendapatan tunai rata-rata rumah tangga buruh tani (dari semua sumber) adalah Rs. 1.686 sementara itu Rs. 1.333 untuk rumah tangga petani miskin di daerah basah. Pendapatan ini berkisar antara Rs. 1.217 dan Rs. 1.103 untuk rumah tangga buruh dan tani miskin masing-masing di daerah kering. Dengan demikian, celahnya lebih banyak di daerah basah dibandingkan dengan di daerah kering.
Terlepas dari temuannya yang agak campur aduk, studi Tamil Nadu oleh Athreya dan rekan-rekannya menyoroti tren yang jelas dalam struktur kelas yang muncul dan ketidaksetaraan atau perbedaan sosial yang menyertainya. Ternyata, jumlah proletariat pedesaan di desa-desa basah dan kering tidak jauh berbeda. Namun, polarisasi yang lebih tinggi di area basah tercermin dalam komposisinya. Lebih dari 60 persen proletariat pedesaan di daerah basah tidak mengolah tanah apapun. Di sini, kaum tani miskin adalah minoritas sementara keadaan sebaliknya di daerah kering. Di sana hanya 36 persen buruh tani yang tidak mengolah tanah dan petani miskin merupakan mayoritas.
Perbedaan kualitatif semakin memperkuat disparitas antara buruh tani di lahan kering dan lahan basah. Proletariat pedesaan di daerah basah adalah tenaga kerja yang lebih terspesialisasi dengan pendapatan non-pertanian yang lebih sedikit, dengan bentuk organisasi kerja yang lebih tinggi (sistem geng, dll.) yang kurang lebih tidak ada di desa-desa zona kering. Perbedaan yang paling mencolok terlihat pada ukuran kaum tani menengah antara daerah kering dan basah yang dicakup oleh studi Tamil Nadu. Di daerah basah, hanya 21 persen termasuk dalam kategori ini berbeda dengan hampir setengah (46%) penduduk agraris yang termasuk dalam kategori petani sedang di daerah kering.
Sifat struktur kelas yang terpolarisasi di daerah basah ini juga tercermin dalam fakta bahwa 14 persen penduduk pedesaan yang mengesankan di daerah basah adalah ‘pengambil kelebihan’ (baik petani kaya, petani kapitalis, tuan tanah penggarap atau tuan tanah murni). . Proporsi ‘penyita surplus’ di daerah basah hampir tiga sampai empat kali lebih tinggi daripada di daerah kering. Proses polarisasi yang menonjolkan perbedaan kelas pedesaan semakin diintensifkan oleh revolusi hijau. Jumlah buruh tani dan proporsinya terhadap penduduk pedesaan telah meningkat di sebagian besar wilayah. Banyak penyewa kehilangan tanah mereka karena tuan tanah dapat mengusir mereka termasuk petani bagi hasil.
Sebuah studi longitudinal tingkat mikro di dua desa dari distrik Mandya di Karnataka, yang dilakukan pada dua titik waktu yang berbeda—1955 dan 1970—juga mengungkapkan perbedaan pertumbuhan tertentu. Di sini, Scarlett Epstein telah menemukan bahwa ketika fasilitas irigasi diperluas ke dua desa, rata-rata kepemilikan yang dimiliki kasta atas Lingayat dan kasta petani tradisional terus meningkat sedangkan persentase tanah milik rumah tangga Adikarnataka (kasta terjadwal) sebenarnya menurun . .
Lahan basah juga telah menarik orang luar (non-petani dari kota terdekat) untuk menginvestasikan modal untuk membeli pertanian. Di dua desa Kar nataka, Epstein juga memperhatikan bahwa masyarakat koperasi pedesaan, khususnya masyarakat kredit, melayani “petani kaya lebih baik daripada petani miskin. Petani kaya mengendalikan lembaga koperasi bukan untuk mendapatkan ‘status’ secara simbolis, tetapi untuk melayani kepentingan pribadi mereka. Yang terkaya dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dari koperasi dengan tingkat bunga resmi 6 persen yang hanya setengah dari tingkat yang dikenakan oleh pemberi pinjaman swasta. Petani kaya juga dilaporkan berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk membeli pupuk dalam jumlah besar secara kredit dan dengan demikian menjamin panen yang baik daripada petani yang lebih miskin”.
Distribusi pendapatan yang buruk di antara rumah tangga pedesaan dari Punjab yang dipelajari oleh Bhalla dan Chadha menunjukkan perbedaan yang serupa atau bahkan lebih mencolok. Survei mereka menemukan bahwa total pendapatan pertanian (bisnis) tahunan dari rumah tangga petani terkecil (yaitu, petani marjinal yang memiliki lahan kurang dari 2,5 acre) adalah Rs. 1.231 sedangkan yang terbesar (dengan kepemilikan operasional di atas 25 acre) adalah Rs. 24.283.
Disparitas kedua pendapatan ditemukan dalam rasio 1:20. Dengan kata lain, petani kecil yang tidak kalah produktifnya dengan petani terbesar, dan yang seluruh keluarganya harus bekerja di ladang, jauh lebih miskin daripada petani yang hampir tidak pernah melakukan pekerjaan kasar sendiri. Patut dicatat dalam temuan studi Punjab bahwa petani marjinal bekerja lebih keras untuk menambah pendapatan mereka melalui sumber non-pertanian seperti peternakan sapi perah, peternakan unggas, dll. Jadi, rata-rata pendapatan non-pertanian dari petani terkecil (per kapita) adalah Rs 392,53 tetapi petani terbesar hanya Rs. 352.84.
Sebagai persentase dari total pendapatan rumah tangga, 64,84 (sekitar 65) persen dari pendapatan rumah tangga petani marjinal berasal dari kegiatan non-pertanian dibandingkan dengan hanya 12,84 persen dalam kasus petani terbesar. Yang sama menariknya adalah kenyataan bahwa meskipun pendapatan bisnis pertanian dari petani terkecil adalah dua puluh kali lebih rendah dari yang terbesar, investasi bruto aset pertanian per acre yang dioperasikan petani adalah sekitar Rs. 60 dibandingkan dengan Rs. 85 untuk petani terbesar.
Dengan demikian, petani yang paling marjinal di Punjab memiliki sekitar 5 persen dari total pendapatan rumah tangganya untuk peningkatan aset pertaniannya; dalam kasus petani terbesar bahkan kurang dari setengah persen. Kecenderungan mengambil risiko dari petani kecil dan marjinal terlalu jelas di sini untuk membutuhkan komentar yang lebih terperinci.
Data Punjab dengan demikian menunjukkan bahwa petani kecil dan marjinal tidak kalah giatnya dengan petani kaya. Yang pertama lebih rentan terhadap pengambilan risiko dalam operasi pertanian mereka daripada yang terakhir ketika sebagian besar pendapatan rumah tangga petani sebenarnya berasal dari sumber dan kegiatan non-pertanian. Hal ini menunjukkan, seperti yang dikatakan Satya Deva, “bahwa distribusi tanah yang lebih merata akan (sebenarnya) menghasilkan investasi yang jauh lebih besar di sektor pertanian dan karenanya akan menyebabkan peningkatan produktivitas yang luar biasa.
Kemungkinan peningkatan yang benar-benar revolusioner dalam (produktivitas pertanian yang mengalir dari kesetaraan yang lebih besar dalam pemilikan tanah telah dirindukan (di Punjab)”. Jelas, peningkatan produktivitas ini akan lebih besar daripada yang telah dicapai sejauh ini di disebut daerah revolusi hijau di mana baik kebijakan maupun praktik telah memihak petani kaya.
Ketidaksetaraan pedesaan mulai membuka dimensinya yang sampai sekarang tidak diketahui jika kita melihat beberapa statistik tentang sambungan listrik di pertanian pertanian yang dengan jelas menunjukkan bagaimana hanya kebutuhan petani kaya yang dipenuhi oleh papan listrik berdasarkan prioritas. Misalnya, Dewan Listrik Punjab memiliki sistem penyediaan sambungan prioritas dengan pembayaran sebesar Rs. 10.000 yang kemudian dikurangi menjadi Rs 7.000 beberapa tahun yang lalu. Sangat menarik untuk dicatat bahwa komite ahli yang membahas tarif listrik untuk konsumen pertanian di Punjab menyadari fakta bahwa sekitar 67 persen dari 10,27 lakh operator pertanian di Punjab memiliki kepemilikan lahan di bawah 4 hektar, dengan ukuran rata-rata kepemilikan lahan sebesar 1,74 hektar saja.
Perkiraan departemen ekonomi dan sosiologi Universitas Pertanian Punjab untuk tahun 1981-1982 menunjukkan bahwa lahan seluas ini (1,74 hektar) mampu menghasilkan pendapatan rata-rata Rs. 7.000 per tahun—jumlah yang kira-kira setara dengan tingkat pendapatan pemeliharaan untuk rata-rata keluarga beranggotakan enam orang. Tetapi ini juga merupakan jumlah yang dibebankan Dewan Listrik di Punjab untuk penyediaan sambungan berdasarkan prioritas. Setidaknya komite ahli yang disebutkan di atas menemukan bahwa pada tahun 1983-1984 hanya ada 3,5 lakh konsumen (sambungan pertanian) yang merupakan hanya sedikit di atas 14 persen dari total konsumen di seluruh Punjab.
Oleh karena itu, dapat diringkas bahwa hanya sekitar 35 persen dari total pemilik pertanian yang mencari sambungan layanan dari Dewan Listrik dan bahwa ini pasti sebagian besar adalah petani kaya yang mampu membayar biaya sambungan atau pemasangan layanan yang tinggi. Petani kecil dan marjinal berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena sangat sedikit dari mereka yang mampu mengeluarkan biaya untuk sambungan listrik dan solar. Penting untuk dicatat dalam konteks ini bahwa survei Punjab oleh Bhalla dan Chadha menemukan pengeluaran listrik berkorelasi positif dengan ukuran pertanian.
Masalah Mekanisasi:
Mekanisasi operasi pertanian di daerah revolusi hijau tidak diragukan lagi telah memperkuat posisi ekonomi petani kaya pedesaan di India. Namun, bagi buruh tani tak bertanah, beberapa dampak buruk dari modernisasi teknologi pertanian terlalu merusak. Dalam beberapa kasus mereka hanya bencana. Tingkat mekanisasi pertanian telah melampaui semua ekspektasi di Punjab sedemikian rupa sehingga di 12.000 desa di negara bagian itu terdapat sebanyak 2 lakh mesin pertanian dari berbagai jenis terutama perontok gandum dan pemanen gabungan. Tetapi efek mekanisasi terlihat dalam kenyataan bahwa ada total 5.000 kematian di India akibat kecelakaan mesin pertanian pada tahun 1978; dari 500 ini saja berasal dari Punjab. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan lebih lanjut bahwa setiap tahun lebih dari 300 pekerja pertanian lumpuh selama musim panen gandum di Punjab.
Sebagian besar kecelakaan ini terjadi saat pekerja bekerja di perontok gandum. Diperkirakan lebih lanjut bahwa pada tahun 1985 (satu tahun saja) hampir 1.000 pekerja pertanian di Punjab, Haryana, dan UP barat kehilangan anggota tubuh mereka karena kecelakaan pengirik. Sebagian besar korban adalah buruh migran. Diperkirakan pada akhir tahun 1985 lebih dari 10.000 buruh tani dari Bihar, UP dan Orissa menjadi cacat saat mengerjakan mesin-mesin tersebut. Menurut informasi resmi yang diberikan di Majelis Punjab pada tanggal 7 September 1978, 841 kasus kehilangan anggota badan atau nyawa terjadi selama tahun 1975 sampai 1978; delapan buruh tani tewas dan 24 kehilangan dua atau lebih anggota tubuh.
Sikap pemerintah terhadap masalah perawatan dan rehabilitasi korban kecelakaan pada mesin pertanian, bagaimanapun, adalah ambivalensi total. Di Punjab, misalnya, Undang-Undang Kompensasi Pekerja tahun 1923 belum dilaksanakan dengan baik. Undang-undang ini menyediakan bagi petani untuk mengasuransikan pekerja mereka terhadap kecelakaan. Buruh tani yang diasuransikan seharusnya mendapatkan Rs. 15.000 untuk kehilangan anggota tubuh. Sebaliknya pemerintah memberikan ganti rugi yang biasanya hanya sepertiga dari jumlah tersebut. Baik pemerintah mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah petani menggunakan mesin perontok di bawah standar, juga tidak berlaku bagi mereka untuk memberikan kompensasi yang sah dan memadai kepada para korban atau untuk melindungi calon korban dari bahaya semacam itu.
Pemerintah dengan jelas mengadopsi sikap keibuan terhadap petani kaya yang dilindunginya tetapi tidak menganggap perlu untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Kompensasi secara ketat dan lembut sehubungan dengan buruh tani yang terluka atau lumpuh dalam kecelakaan mesin. Bahaya kesehatan bagi buruh tani pedesaan di sabuk revolusi hijau tidak terbatas pada ketidakmampuan akibat kecelakaan mesin. Pekerjaan pertanian di daerah ini semakin berbahaya dengan meningkatnya penggunaan semprotan kimia beracun untuk perlindungan tanaman dalam skala besar.
Varietas benih unggul—digunakan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi revolusi hijau—tampaknya sangat rentan terhadap penyakit, dan di negara-negara dunia ketiga pestisida beracun digunakan baik secara ekstensif maupun intensif untuk perlindungan tanaman tanpa menyadari bahaya kesehatan yang ditimbulkannya. mengikuti untuk tenaga kerja pertanian.
Sebuah laporan baru-baru ini dari Pusat Penelitian Pembangunan Internasional, Ottawa telah mengungkapkan bahwa ada 7,5 lakh kasus keracunan akut dengan berbagai jenis pestisida. Setengah dari ini dilaporkan dari negara-negara dunia ketiga, yang sepertiga lagi dilaporkan dari India saja. Korban keracunan semacam itu selalu adalah buruh tani, dan jarang sekali petani kaya itu sendiri.
Misalnya, sebuah penelitian terhadap 70 pasien keracunan akut yang dilaporkan dari rumah sakit sipil Vadodara dan Surat (di Gujarat) dalam tiga tahun dari tahun 1976 hingga 1978 semuanya adalah buruh tani, termasuk dua wanita. Anehnya, tidak ada perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kecelakaan keracunan di pertanian pertanian karena Undang-Undang Kompensasi Pekerja hanya berlaku untuk pekerja industri dalam hal ini.
Membandingkan distribusi pendapatan dan unit konsumsi baik petani kaya pedesaan (magnates) dan rumah tangga buruh tani pada tahun 1955 dan pada tahun 1970, Epstein menyimpulkan bahwa yang kaya menjadi lebih makmur dan yang miskin menjadi lebih miskin. Upah riil pertanian telah menurun terutama karena peningkatan jumlah rumah tangga tenaga kerja, dan kenaikan harga yang stabil mengakibatkan kenaikan biaya hidup. Upah, bagaimanapun, telah tertinggal. Beberapa sarjana lain, yang telah meneliti dampak revolusi hijau pada golongan yang lebih lemah, berpendapat dengan agak optimis, bahwa kondisi kaum miskin pedesaan—khususnya tenaga kerja pertanian—tidak serta merta memburuk.
Sebaliknya, kemakmuran umum yang dibawa oleh modernisasi pertanian di daerah revolusi hijau, meresap ke akar rumput masyarakat pedesaan . Di mana proses perkolasi ini ditangkap oleh orang kaya melalui manipulasi dan intrik, buruh tani di sana cenderung menjadi lebih terorganisir dan lebih militan untuk berjuang dan dengan demikian memperoleh keuntungan melalui upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.
Dengan demikian, tawar-menawar kelompok memperkuat posisi tenaga kerja pertanian dalam persamaan kekuatan pedesaan. Namun, optimisme ini didasarkan pada asumsi persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja. Bahkan, dengan kondisi pasar tenaga kerja yang tidak sempurna, seperti yang diperoleh di India, daya tawar tenaga kerja pedesaan lebih terlihat daripada nyata.
Ada juga asumsi lain bahwa revolusi hijau pasti menaikkan laju pertumbuhan pertanian di daerah yang terkena dampak. Tetapi beberapa sarjana bahkan mempertanyakan asumsi ini. Setidaknya beberapa ahli ekonomi memberitahu kita bahwa di India produksi pertanian tumbuh paling baik pada tingkat rata-rata konstan selama periode 1950-51 sampai 1973-74; paling banter revolusi hijau mungkin berhasil menahan kecenderungan ke arah penurunan produksi/tingkat pertumbuhan pertanian yang diamati pada akhir 1950-an (Reddy, 1978). proses de-peasantisasi telah dipercepat dan akibatnya sejumlah besar petani kecil dan marjinal atau petani miskin telah terdesak menjadi buruh tak bertanah (Oommen, 1975: 175).
Proses proletarisasi ini lebih mencolok di daerah revolusi hijau. Mengingat proses proletarisasi ini, perbaikan yang diharapkan akan dibawa oleh revolusi hijau ke dalam kondisi pekerja upahan tampaknya merupakan fatamorgana yang jauh. Setidaknya posisi kaum miskin pedesaan—khususnya pekerja pertanian budaya—sebagai sebuah kelas tidak mungkin diubah secara substansial vis-a-vis para petani kaya yang secara virtual memonopoli sumber daya ekonomi dan mengendalikan lembaga kredit di pedesaan (Palmer, 1976 ; Dhanagare, 1984: 192-93; juga Bagchi, 1982: 176).
Secara umum, temuan dari studi yang berbeda menunjukkan bahwa revolusi hijau memiliki dampak yang kontradiktif terhadap lapangan kerja pedesaan dan upah pertanian. Pesimisme Grup Halslemere atau skeptisisme Reddy terhadap potensi revolusi hijau dalam meningkatkan laju pertumbuhan pertanian dapat dikesampingkan untuk sementara.
Seseorang dapat dengan murah hati mengakui bahwa dengan meningkatkan produktivitas tanah dan dengan memungkinkan para petani untuk menanam dua atau bahkan tiga jenis tanaman di sebidang tanah, revolusi hijau telah memungkinkan para pekerja pedesaan memperoleh lebih banyak pekerjaan untuk tahun itu. semua. Tetapi kemudian Billings dan Singh menemukan bahwa di Punjab permintaan tenaga kerja pertanian naik dari 51 hari kerja menjadi 60,1 hari kerja dengan diperkenalkannya roda persia sebagai alat irigasi dan pupuk serta pestisida.
Namun, ketika pompa, perontok gandum, pemipil jagung dan traktor diperkenalkan, permintaan rata-rata untuk tenaga kerja turun menjadi 25,6 hari kerja. Di bagian tertentu yang makmur seperti di Haryana, revolusi hijau telah menyebabkan penggantian hubungan paternalistik antara pengusaha petani kapitalis dan pekerja dengan kontrak formal (Bhalla, 1976); tetapi di sebagian besar bagian lain negara buruh terikat hanya dikeluarkan dari pekerjaan atau diubah menjadi buruh harian lepas (Gough, 1977).
Di mana mekanisasi operasi pertanian tampaknya mencerahkan kesempatan kerja dan upah di daerah revolusi hijau, migrasi pekerja dari daerah yang kurang disukai—seperti Bihar, UP timur, Orissa atau Rajasthan—cenderung menekan posisi tawar serta upah. Pola konsumsi di daerah revolusi hijau juga sangat mencolok dan angka penduduk di bawah garis kemiskinan sangat tinggi. Kasus Punjab—negara bagian paling makmur di India—sekali lagi memberikan sinyal merah.
Kajian Bhalla-Chadha mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga dari petani marjinal (bercocok tanam hingga 2,5 acre), seperempat dari petani kecil (antara 2,5 dan 5 acre) dan seperlima dari petani tingkat menengah (budidaya kepemilikan). antara 5 dan 7,5 acre) dari sampel mereka hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu hidup dengan diet kelaparan.
Dalam total sampel 1.663, 16,48 persen rumah tangga petani hidup di bawah garis kemiskinan dan proporsinya berkorelasi positif dengan ukuran pertanian di ketiga wilayah Punjab. Jika kita menambahkan 16 persen rumah tangga buruh tani, maka proporsi rumah tangga pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai lebih dari 32 persen yang menyedihkan mengingat Punjab adalah negara bagian paling maju di India.
Hal ini akhirnya menimbulkan keraguan akan keampuhan teknologi revolusi hijau yang semula divisualisasikan sebagai langkah pengentasan kemiskinan. Karena revolusi hijau diproyeksikan sebagai ideologi resmi baru untuk rekonstruksi pedesaan agar dapat memerangi kemiskinan secara efektif, penting untuk memeriksa di sini apakah implementasi dan konsekuensinya telah memfasilitasi pengentasan kemiskinan atau apakah ia telah menghentikan proses menjembatani kesenjangan antara bagian yang makmur dan yang lebih lemah yang mewakili dua ujung ekstrim dari spektrum pembangunan di India.
Nyatanya, semua statistik yang tersedia menunjukkan semakin banyak kebosanan dan kemiskinan karena paket teknologi revolusi hijau telah menyebar di berbagai bagian India. Studi tentang kemiskinan, yang diukur dengan pengeluaran per kapita dan konsumsi kalori di India, lebih jauh mengungkap kekosongan klaim yang sering dibuat oleh para perencana dan pelaku revolusi hijau. “Proses pembangunan pedesaan selama dasawarsa 1960-69 lebih menguntungkan golongan menengah ke atas dan golongan terkaya daripada golongan menengah, menengah ke bawah dan golongan termiskin”.
Akibatnya, ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan India terus meningkat. Sementara Dandekar dan Rath menemukan sekitar 45 persen dari total populasi berada di bawah garis kemiskinan pada harga tahun 1960-61, Bardhan tampil dengan gambaran yang bahkan lebih suram. Dia membandingkan proporsi penduduk pedesaan di bawah tingkat hidup minimum (didefinisikan sebagai Rs. 15 per bulan dengan harga tahun 1960-61) pada tahun 1960-61 dengan tahun 1967-68.
Tanpa pengecualian, semua negara bagian India mengalami peningkatan besar-besaran dalam persentase penduduk pedesaan di bawah garis kemiskinan. Ini berkisar antara 80 hingga lebih dari 84 persen di negara bagian seperti Bihar, Orissa, UP dan Benggala Barat pada tahun 1967-68. Bahkan di negara bagian yang paling makmur, angka itu naik dari 25,01 menjadi 63,97 persen di Gujarat, dari 40,14 menjadi 67,61 persen di Maharashtra dan dari 13,56 menjadi 49,98 persen di Punjab. Jadi, di jantung revolusi hijau (Punjab-Haryana) yang berdenyut, persentase ini meningkat hampir empat kali lipat antara 1960-61 hingga 1967-68.
Tren ini dikonfirmasi satu dekade kemudian (setelah studi Bardhan) oleh studi lain yang dilakukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional pada tahun 1979. Mengambil sampelnya dari empat negara bagian Punjab, Tamil Nadu, Bihar dan UP, survei ini ditujukan untuk menentukan tren secara absolut dan pendapatan relatif penduduk miskin pedesaan. Ini mengungkapkan distribusi pendapatan yang terus memburuk dan pendapatan riil masyarakat miskin pedesaan yang menurun. Di tanah pertanian yang kaya di Punjab, pendapatan riil per kapita dilaporkan meningkat sebesar 26 persen selama tahun 1960-an (dua setengah kali lebih cepat dibandingkan di India secara keseluruhan). Meskipun demikian, proporsi penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat di Punjab dari 18 persen pada tahun 1960 menjadi 23 persen pada tahun 1970.
Di Tamil Nadu, studi ILO menemukan bahwa persentase penduduk yang berpenghasilan kurang dari biaya yang diperlukan untuk garis makanan minimum telah meningkat dari 36,04 persen pada tahun 1961-62 menjadi 48,63 persen pada tahun 1969-70. Mempertimbangkan ‘garis kebutuhan dasar’ , persentase ini telah naik dari 66,49 menjadi 73,98 untuk tahun-tahun yang sesuai. Tentang asal-usul sosial masyarakat miskin pedesaan, survei ILO mengungkapkan bahwa di semua negara bagian, para buruh tani—keluarga tak bertanah dan hampir tak bertanah—yang merupakan inti dari kemiskinan pedesaan. Misalnya, di Tamil Nadu pada tahun 1971, 56 persen dari semua petani, 85 persen ‘pekerja lain’ (terutama pengrajin) dan 87 persen buruh tani hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun, beberapa ekonom telah memberi kita gambaran yang lebih optimis. Menggunakan data dari putaran ke-32 (revisi 1977-78) dan putaran ke-38 (1983-84) Survei Sampel Nasional (NSS), Hanumantha Rao menunjukkan bahwa penurunan jumlah orang di bawah garis kemiskinan untuk semua populasi diperkirakan sekitar 12,5 persen di daerah pedesaan dibandingkan 7,8 persen di daerah perkotaan. Dia, bagaimanapun, menerima bahwa antara 1977-78 dan 1983-84 penurunan ini kurang menonjol untuk kasta dan suku yang dijadwalkan (masing-masing 7,6% dan 7,1%) dibandingkan dengan 15,1 persen untuk sisa populasi yang tingkat penurunannya dalam rasio kemiskinan lebih dari dua kali lipat tingkat untuk kasta dan suku yang dijadwalkan.
Bahkan dengan asumsi bahwa kesimpulan Hanumantha Rao mendekati kenyataan, mereka menyiratkan pengakuan bahwa program pengentasan kemiskinan, apakah IRDP atau NREP (Program Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional), telah gagal membawa pengurangan yang cukup besar dalam rasio kemiskinan pedesaan di negara yang sangat maju seperti Punjab antara tahun 1977-78 dan 1983-84 rasio kemiskinan hanya menurun sebesar 17,1 persen.
Kinerja buruk Punjab dalam program pengentasan kemiskinan menjadi lebih mencolok mengingat fakta bahwa (a) rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita adalah yang tertinggi (81,69 dibandingkan dengan rata-rata seluruh India sebesar 70,94) di Punjab; dan (b) bahwa pengeluaran untuk program anti-kemiskinan (pengentasan kemiskinan) seperti IRDP, NREP, dll., untuk tahun 1980-84 adalah yang tertinggi di negara bagian itu—-31,22 untuk Punjab dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 8,33 .
Dua poin muncul dengan jelas dalam analisis Hanumantha Rao:
Pertama, bahwa meskipun program pengentasan kemiskinan telah berhasil membawa penurunan yang berarti dalam proporsi penduduk pedesaan di bawah garis kemiskinan, kinerja mereka jauh kurang mengesankan untuk kasta dan suku yang dijadwalkan—bagian masyarakat India yang secara tradisional lebih lemah. ; dan
Kedua, variasi regional dalam penurunan rasio kemiskinan pedesaan jelas menunjukkan bahwa negara bagian yang lebih maju khususnya Pun jab tidak berkinerja memuaskan seperti beberapa negara bagian yang kurang berkembang seperti Madhya Pradesh, Orissa dan Benggala Barat.
Implikasi dari poin-poin ini terlalu jelas untuk membutuhkan elaborasi apapun. Pertumbuhan pertanian mungkin diperlukan tetapi bukan kondisi yang cukup untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan pendapatan. Kemauan politik yang lebih tulus dan komitmen terhadap filosofi keadilan distributif harus sesuai dengan tingkat pertumbuhan budaya pertanian yang meningkat—sebuah diktum yang hampir diabaikan dalam perencanaan India untuk pembangunan pedesaan.
Ada ekonom lain yang tidak memiliki optimisme yang sama dengan Hanumantha Rao tentang dampak langkah-langkah pengentasan kemiskinan, juga tidak menerima versi resmi dari apa yang disebut sebagai pencapaian IRDP atau NREP. Sebagai contoh, Rath telah berusaha untuk menunjukkan kegagalan multifaset IRDP/NREP dan bahkan berkomentar bahwa seharusnya tidak mengejutkan jika survei NSS lain tentang pengeluaran konsumsi pada pertengahan 1980-an tidak menunjukkan dampak yang terlihat dari IRDP pada dimensi pendapatan. kemiskinan pedesaan di India. Pandangan serupa diungkapkan sebelumnya oleh Raj Krishna. Baginya, skema IRDP dan NREP hanya membawa manfaat kecil, sering diabaikan, bagi kaum miskin pedesaan; setidaknya ini tidak cukup substansial untuk memastikan bahwa rumah tangga yang sering diklaim oleh sumber resmi telah terangkat di atas garis kemiskinan akan tetap berada di atas garis kemiskinan secara permanen.
Kekhawatiran Raj Krishna sepenuhnya dibenarkan mengingat fakta bahwa Rancangan Rencana (1978-83) telah memperkirakan jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 290 juta pada tahun 1978 sedangkan perkiraan Bank Dunia menyatakan bahwa ada sebanyak 327 juta. miskin pedesaan. Nyatanya, Raj Krishna khawatir bahwa terlepas dari klaim resmi tentang penurunan rasio kemiskinan pedesaan, angka Rencana Lima Tahun Keenam dari populasi miskin (339 juta di bawah garis kemiskinan) untuk tahun 1980 akan tumbuh menjadi 472 juta pada akhir abad ini. yang akan lebih dari populasi India pada saat kemerdekaan.
Selama hampir dua dekade sekarang langkah-langkah revolusi hijau telah dicoba oleh negara bagian di berbagai bagian India. Tak hanya itu, atas nama penyebarluasan teknologi revolusi hijau, bahkan transnasional diizinkan beroperasi di pedesaan melalui kedok resmi.
Namun, di sebagian besar wilayah, revolusi hijau telah gagal meningkatkan pendapatan kaum miskin pedesaan secara berarti, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi daya beli mereka yang efektif. Sebaliknya, di banyak bagian, pendapatan riil buruh tani dan petani miskin lebih rendah pada awal tahun 1970-an dibandingkan pada tahun 1960-61. Beberapa penelitian di Punjab, UP, Bihar dan Tamil Nadu telah menghasilkan data yang meyakinkan mengenai hal ini.
Dorongan utama revolusi hijau adalah menuju produktivitas dan pertumbuhan. Para pembuat kebijakan terutama memperhatikan peningkatan hasil per acre. Asumsi yang mendasari prioritas perencana adalah bahwa pertumbuhan itu sendiri sudah cukup karena akan menunjukkan efek perkolasi dan pada gilirannya akan membantu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di pedesaan India.
Perspektif ini sekarang berdiri hampir didiskreditkan. Alternatifnya, perspektif lain sedang diadvokasi yang tidak memperlakukan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan sebagai dua tujuan yang berbeda tetapi percaya bahwa yang terakhir harus dibangun ke dalam proses pertumbuhan. Pendekatan ini menganjurkan sosialisasi aset produktif dan distribusi yang lebih egaliter dari fasilitas infrastruktur ini melalui promosi kegiatan koperasi.
Garis-garis pemikiran sosialistik terlihat jelas dalam perspektif baru tentang pembangunan pedesaan di India. Namun, gagasan untuk reorientasi dan reorganisasi IRDP, dll., jarang melampaui saran untuk desentralisasi pengambilan keputusan, mempercayakan badan panchayat (zilla parishad) dengan tanggung jawab untuk perencanaan dan pemantauan keseluruhan program anti-kemiskinan, atau untuk mengubah alokasi rencana prioritas, “untuk beralih dari pendekatan individu ke kelompok”—apa pun artinya.
Jarang kita memeriksa kecukupan dan kesesuaian kerangka konstitusional yang memperlakukan institusi kepemilikan pribadi sebagai hal yang sakral, dan menganggap kepemilikan, dan bukan pekerjaan, sebagai hak fundamental. Pertanyaan yang relevan adalah apakah dan sejauh mana kerangka kelembagaan yang ada kondusif bagi perubahan sistemik—yang sering ditawarkan sebagai pereda nyeri dalam diskusi populis tentang pembangunan pedesaan dan kemiskinan.
Dominasi yang tumbuh dari kelas baru petani kaya adalah fakta yang harus diperhitungkan dan tidak bisa disingkirkan. Bahkan naif untuk percaya bahwa revolusi hijau dan langkah-langkah IRDP (untuk pengentasan kemiskinan) merupakan titik di mana pertumbuhan dan keadilan sosial menyatu dan menyatu dan bahwa kedua tujuan tersebut dapat ditargetkan secara bersamaan tanpa restrukturisasi fundamental dalam institusi properti. Tanpa memikirkan kembali strategi pembangunan untuk perubahan mendasar dalam sistem, ketimpangan pedesaan tidak akan berkurang apalagi dihilangkan.